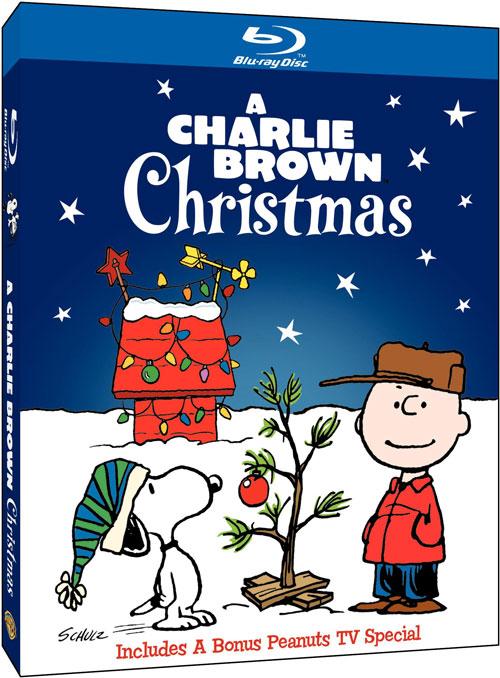Ijinkan aku bercerita kepadamu kawan.
Tentang sebuah negeri tak jauh dari tempatmu berdiri.
Negeri dengan budaya dan tradisi yang telah lama terpatri.
Negeri yang telah selesai menempatkan sang jati diri.
Ijinkan aku mengingatkanmu kawan.
Bahwa negeri ini telah ada sebelum negerimu,
semangat kamilah yang meniup bara untuk api penggerak negerimu,
keikhlasan kamilah yang rela menjadi pupuk tumbuh suburnya negerimu,
kamilah ibu yang menyusuimu kala kau bahkan belum sanggup berdiri sendiri,
uluran tangan kamilah yang menuntunmu menuju langkah-langkah pertamamu.
Kami tak menuntut kau sebut kami yang terhebat,
Kami tak minta kau bayar seluruh hutang budi,
Karena jiwa kami adalah jiwa seorang ibu,
Kami hanya tahu mengasihi,
namun kami juga bisa sakit hati, kawan.
Negeri ini, tempat manunggaling kawula gusti.
Maka jangan heran betapa kami tidak menakar hubungan kawula dan gusti dengan harta duniawi.
Interaksi kami bukan proses jual beli.
Seperti inilah kami selalu dididik dan diajari.
Betapa syukur kami punya pemimpin yang hamengku dan hamengkoni, memangku kami, kawulanya.
Pemimpin kami TIDAK menduduki tahta, kawan. Karena di negeri ini tahta adalah untuk rakyat.
Maka jangan kau herani, tatkala kami serentak membela pemimpin kami, karena ketahuilah kawan, sebenar-benarnya kamilah yang terlebih dahulu dibela. Kami yang ’hanya’ kawula ini. Kami ini punya harga diri, kawan.
Mungkin ini yang tak kau mengerti kawan.
Karena nalarmu telah tersumpal, otakmu menjadi bebal, tersaput oleh ambisimu sendiri. Ambisi yang nyaris menjadi sebuah obsesi. Oleh kepentingan kotor yang terbungkus manis dalam sebuah misi ’menegakkan demokrasi’. Oh, betapa seakan sungguh indah label itu kawan. Namun di tengah kecongkakanmu berdiri disana, betapa kau lupa banyak hal kawan. Kau lupa jati dirimu, jati diri negerimu. Hatimu pun seakan kebas, tak mampu merasa. Matamu pun buta, telingamu tuli. Tak kau dengar jeritan kami, tak kau lihat keinginan kami. Dan siapa sekarang yang sebenarnya monarki kawan? Kala kau berdiri disana, bagai seorang raja, bagai seorang kaisar, dengan kata yang tampaknya tak terbantahkan.
Kami disini, di negeri tentram damai ini,
kami menolak cara yang kau titahkan, yang hendak kau injeksi paksa ke dalam tatanan kami.
Kami menolak konsep demokrasi yang kau tawarkan. Karena kawan, orang buta pun tahu, semanis apapun mulutmu bicara, demokrasi uanglah yang akan terterapkan. Kau ini lupa kawan, bahkan bukan cara itu yang dipakai oleh negerimu untuk menerapkan sebuah demokrasi. Jadi kini, bercerminlah kawan, siapa sebenarnya sang pengkhianat konstitusi? Inilah kawan akibat demokrasi komersial yang kau terapkan, yang dahulu mendongkrakmu naik ke tahta yang kau duduki sekarang, kau merasa kau sudah membeli suara rakyatmu, jadi kau berhak berbuat semaumu. Betapa kejamnya kini sebaliknya : kau berikan cap bahwa kami ini pelanggar konstitusi, dan anti demokrasi.
Ijinkan kami mengambil sikap kawan.
Dengan kesantunan dan kebersatuan, yang mungkin asing kau temui.
Kami telah menentukan sikap kami.
Tidak, kami tidak memohon kawan. Kami berkata kepadamu. Karena seperti sejak sediakala, kami tidak pernah meminta darimu, dari negerimu. Kamilah yang pernah memberimu. Maka kami kini berdiri bersama, bersatu, bulat, mufakat, manunggaling kawula gusti. Inilah bagi kami maknaning demokrasi. Ijinkan kami berkata kepadamu.
Disini, dari sidang rakyat.
Ini bukan sekedar kisah, kawan.
Sebaiknya kau renungkan sebelum tidur malammu, kau insyafkan dalam istighfarmu.
Karena ini bukan sekedar kisah.
Kami bukan sekedar kisah. Kami yang berdiri disini saat ini.